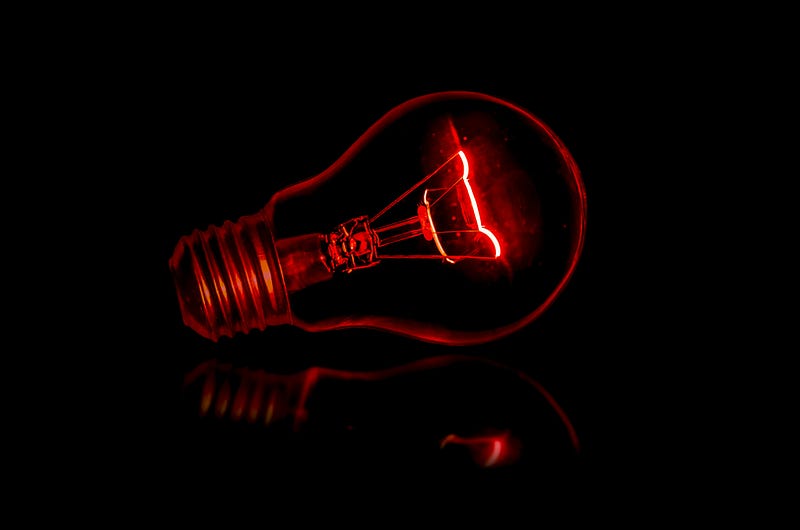
Bukan mau mengakali, kehidupan bukan sesuatu yang bisa diakali, karena memang bukan sesuatu. Entah harus disebut apa.
Mungkin lebih mudah jika tidak berakal sama sekali. Mengandalkan insting saja. Lapar makan. Lelah tidur. Sedih menangis. Marah menjelma iblis atau berteriak sekencang-kencangnya. Tidak perlu memikirkan ini itu dan lain hal.
Aku rasa tidak relevan kalimat yang sering kudengar, “Hal menyakitkan yang tidak membuatku mati hanya akan membuatku semakin kuat.”
Jika aku adalah benda elastis, yang bisa melentur dan menyesuaikan diri dengan sempitnya ruang, maka menjadi kuat tidak selalu berkonotasi positif. Dan tidak selalu menandakan kekuatan. Pada akhirnya, semakin kuat aku malah akan semakin rapuh dan riskan. Mudah patah saat dihadapkan dengan lekukan tajam kehidupan.
Namun keduanya juga tidak bisa relevan dengan kenyataan. Karena kenyataan memintaku menjadi udara, yang bisa bergerak atau diam di mana saja, menghimpun dan mengantarkan apa saja, tidak terbatas pada bentuk absolutnya. Karena udara sendiri selalu bernilai relatif. Ukuran yang tidak jelas nilainya tapi jelas mewakilkan perjalanan kehidupan.
Aku … sungguh kehabisan akal.
Anehnya, aku tak bisa menangis. Aku juga tak bisa marah. Atau beralasan ini itu, mengakali ini itu, dan serba-serbi basa-basi layaknya manusia.
Aku hanya … kehabisan akal.
Atau barangkali hanya terlalu malas untuk mengulang lagi, pikiran-pikiran ini, hasrat dan harapan itu, atau ide dan solusi yang coba diraih tapi selalu terasa begitu lambat terealisasi. Meski ribuan hari telah terlewati. Mangulang pemikiran yang sama tak membuatku menjadi pintar. Atau paham. Atau menguasai persoalan kehidupan.
Seperti anak 4 tahun yang sudah bergelar doktor. Mau gelarmu doktor atau beristri banyak, kalau masih 4 tahun ya namanya balita. Sekeras apapun anak 4 tahun berusaha menjadi dewasa, tetap saja balita. Terdengar menyebalkan bukan?
Aku menjalaninya dalam ribuan hari sejak aku sadar hal ini sangat membuatku memendam dendam. Sementara perlahan dendam ini malah bermata dua, menusukku lebih dulu sebelum terbalas.
Mungkin sejak awal kacamataku saja yang tidak cocok. Lensaku salah ukuran. Barangkali karena aku tidak meminta dokter untuk memeriksanya. Mau bagaimana lagi, mataku buram dan di depanku berjalan tergeletak kacamata yang bisa kupakai. Ini sudah lebih baik dari tidak ada sama sekali, meski masih buram, lensa ini membantuku memandang. Dan mungkin inilah akar masalahnya.
Mungkin sebaiknya sekalian tidak ada kacamata, biar buram sekalian, tidak hanya berbayang-bayang. Memberi harapan sementara tidak pernah ada kepastian. Aku bisa saja terjatuh karena percaya bahwa jalanan di depan rata, padahal ada lubang yang tertutup bayang-bayang pohon. Aku melihatnya sebagai bayangan, tapi ternyata dalam, dan aku terperosok.
Mugkin malah berbeda jika tak ada kacamata. Aku bisa lebih percaya pada tongkat kayuku. Meski perlahan, aku pasti akan sadar ada lubang di depan.
Kau tau, ini hanya sebuah persimpangan. Pilihan mana saja, mungkin akan berdampak menyebalkan jika tidak diterima bagaimanapun keadaannya. Namun bagaimana jika persimpangan ini terus bercabang dan bercabang lagi, lagi, dan lagi. Sampai membentuk labirin. Aku mungkin masih bisa berjalan mundur, menyusuri jalan sebelumnya, tapi akan seberapa lama lagi terjebak di labirin ini?
Ratusan menit. Puluhan jam. Ribuan hari. Sampai mengundang bulan-bulan dan berganti tahun-tahun. Masihkah aku akan waras untuk menyusuri labirin ini lagi?
Aku tidak tau. Sekarangpun, rasanya aku telah kehabisan akal.
Aku ingin menangis, tapi ternyata air mata juga tidak keluar. Sebagai gantinya, bibirku malah terangkat, senyum menyebalkan yang mungkin terlihat menakutkan. Perasaanku tak lagi seirama, pikiranku tak lagi teratur. Semua terasa seperti pecahan-pecahan kaca yang licin dan tajam. Jika tak hati-hati, tanganku sendiri yang akan berdarah untuk menyatukannya lagi. Mungkin memang tak perlu aku satukan.
Mungkin aku bisa menyulap diriku menjadi karya seni. Kau tau, karya seni selalu dipenuhi ketidakteraturan. Penuh dengan pelanggaran aturan. Dan selalu memiliki keunikan tersendiri. Namun tak pernah ada yang benar-benar ingin memiliki/merasakan. Mentok hanya menjadi pajangan atau sumber kekaguman, tanpa seorangpun ingin merasakannya sendiri. Menjadi sebuah karya seni abadi.
Aku benar-benar kehabisan akal.
Aku tak pernah benar-benar memahami perasaan. Dan sekarang semakin terasa pudar. Emosi yang kian melemah dan kehilangan maknanya di dalam hati. Entah hanya berhibernasi atau benar-benar mati.
Tubuhku selalu bergetar. Harus terus berbicara sesuatu yang tidak aku pahami. Namun harus disampaikan. Aku tak pandai meramu kalimat yang berisi, karena sumbernya sendiri adalah kehampaan.
Aku mungkin meninggikan suara agar terdengar meyakinkan. Atau melotot karena takut air mata yang keluar. Atau mengepal karena jari-jariku tak bisa diam, terus bergetar. Omong kosong yang terus aku ucapkan membuat jantungku memompa tak beraturan. Sudah. Aku ingin menyudahinya. Tapi tidak bisa.
Aku benar-benar kehabisan akal.
Aku … merindukan sesuatu yang tak pernah dirindukan kebanyakan orang. Aku tak mengerti, tapi rasanya begitu menyebalkan dan menusuk, karena mereka tak pernah menyadari betapa mengganggunya ketidaktahuan mereka.
Apakah orang wajib bertanggung jawab atas apa yang tidak diketahui? Tentu tidak, bukan. Namun bagaimana jika ketidaktahuan itu menyiksaku? Seperti lautan yang hendak membasuh tubuhku, yang lusuh tak mandi berhari-hari, sementara ada ratusan luka terbuka yang semakin perih terasa saat cairan garam menyentuhnya.
Rasanya aku hanya ingin berteriak. Bangsaaaaaat!
Laut, kau kira rasa pedulimu itu benar-benar menyembuhkanku? Membersihkanku?
Aku tak bisa berteriak, karena tubuhku begitu lelah dan sakit. Tentu saja aku hanya diam. Namun tidak bisakah kau mencerap lebih teliti? Gigiku meringis bukan menebar kebahagiaan. Perasaan ini telah membuatku gila.
Aku benar-benar telah kehabisan akal.
Kau diamlah saja, aku akan diam dan tak mengganggumu juga.
Aku, perasaan, dan pikaranku yang entah terlihat seperti apa di matamu.
Kadang aku hanya ingin mengandai apa saja, menumpuk pikiranku yang sudah buncah dengan imajinasi yang menipu akal. Namun keidupan tak bisa dijalani dengan hanya mengandai.
Sebagai makhluk hidup, anak 6 tahun pun tahu bahwa aku harus bernapas, makan, tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Tapi tidak ada keharusan memperhatikan perasaan dan berpikir untuk hidup.
Sementara semakin lama aku hidup, yang semakin jelas menumpuk justru pikiran dan perasaan yang beranekaragam. Konsumsi selalu dibarengi dengan ekskresi. Seperti respirasi, ada yang masuk, ada yang keluar. Namun perasaanku membentuk diriku, membawa puing demi puing seiring berjalannya waktu, tersusun satu persatu dan tumbuh bersama denganku. Dan bila saatnya puing-puing ini telah tersusun tinggi, pikiran akan muncul untuk merelokasi dan membentuknya menjadi sesuatu. Dan tidak ada yang pernah keluar setelah tersusun.
Mungkin aku lupa, tapi tak pernah menghilang, karena ada perasaan yang tersisa. Suatu waktu, barangkali akan membuatku bernostalgia. Suatu waktu, mungkin aku akan menangis karenanya. Suatu waktu, bila aku bisa mempertahankan susunan puing-puing ini, semuanya akan terasa berharga.
Pun suatu waktu, ruang itu akan penuh. Saat itulah kita berhenti tumbuh. Menjadi tua. Menjadi kolot. Menjadi sulit menerima pandangan lain. Menjadi kabur dalam menimbang keputusan baru. Menjadi hal-hal yang menyebalkan untuk mereka dengan ruangan yang masih luas belum terpakai.
Namun bagaimana jika ruangan ini masih luas, tapi puing-puing gagal disusun, berantakan. Aku tak perlu menunggu tua, tak perlu menunggu kolot, dan tak perlu menimbang dari pengalaman di kepala, karena sisanya hanya hampa. Bukan sesuatu yang akan menjadi referensi atau bahan nostalgia.
Tak separah hancur, tapi dengan puing yang berserakan, dengan tubuh yang terjebak di labirin bercabang, dengan waktu yang telah sepertiga usia dilewatkan, dengan pemikiran, perasaan, dan keadaan yang memuakkan, masihkah aku akan waras untuk terus tersenyum dan berjalan santai?
Lucu kan?
Aku akan terus waras. Aku akan terus tersenyum. Dan aku akan terus mendendam. Iri. Ataupun marah. Jika ketidaktahuan itu membuatku sakit, maka akan kugunakan ketidaktahuan yang sama untuk berjalan.
Akan aku tanggalkan kacamata yang kutemukan. Akan aku hilangkan puing-puing yang berserakan di ruangan, biar luas dan penuh dengan gulita kehampaan. Akan aku dengarkan, lalu arungkan bersama angin malam. Akan aku lihat lalu kuserahkan dengan senyuman. Akan aku sentuh lalu kubasuh tangan.
Aku akan tetap waras.
Karena takkan kulibatkan akal terlalu dalam.
Kau tau … karena aku telah kehabisan akal.
Semarang, 16–17 April 2024
Yayan Deka
![[Contoh] 16 Esai Juara Lomba - Download [Contoh] 16 Esai Juara Lomba - Download](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyZVjK6f_uGehFd7roU-VQMjDD38bAe9gIKn6CiqvG1UL49JzMJ1IQboAzSrDw8SluAhjx1ABC85vcVTZjbyuCsAwDenfj-0NfXkmzJTOnIGs5PzPOTMVKVuT_w4J3jaVqVlja6G2uz-8K/s72-w320-c-h183/esai+1.png)


